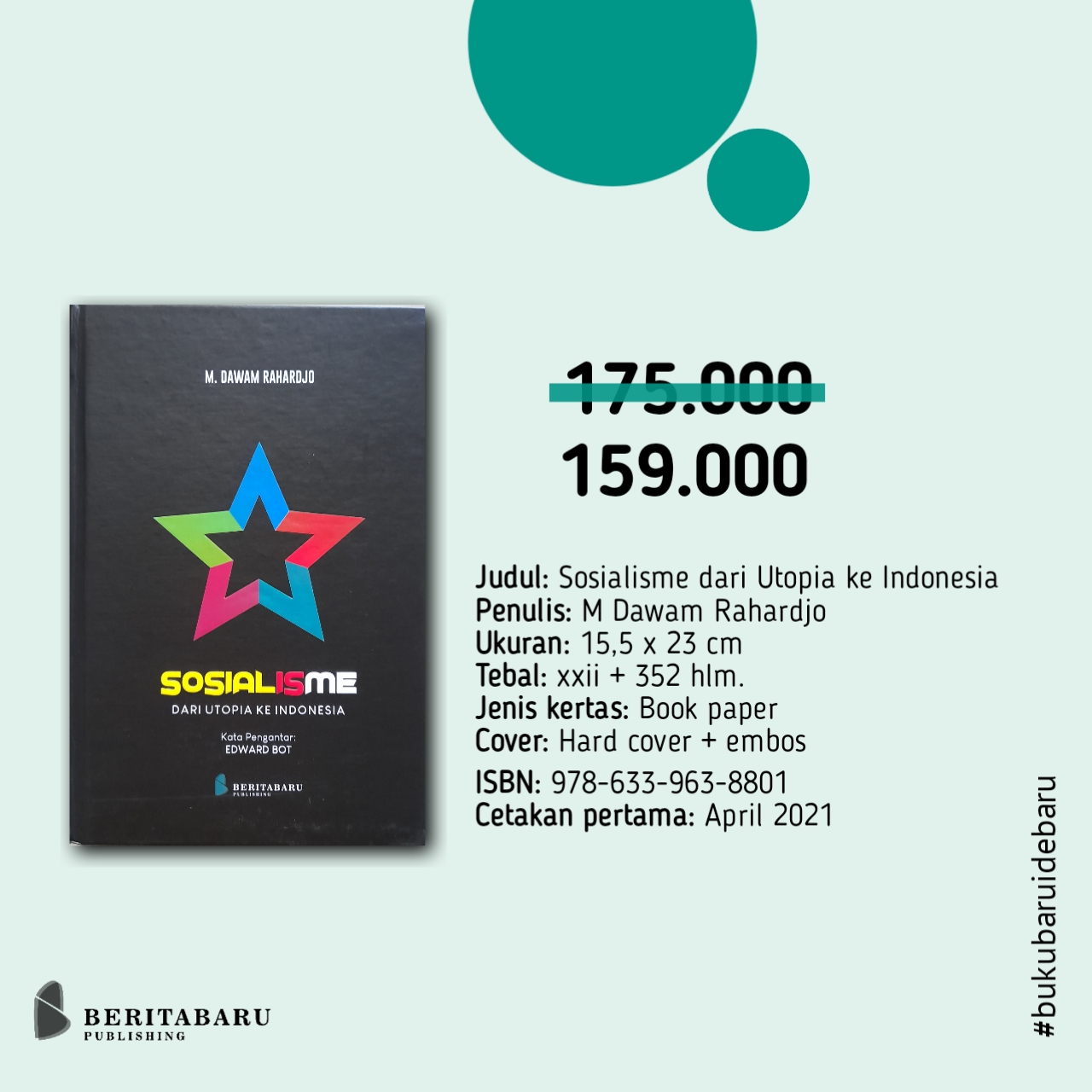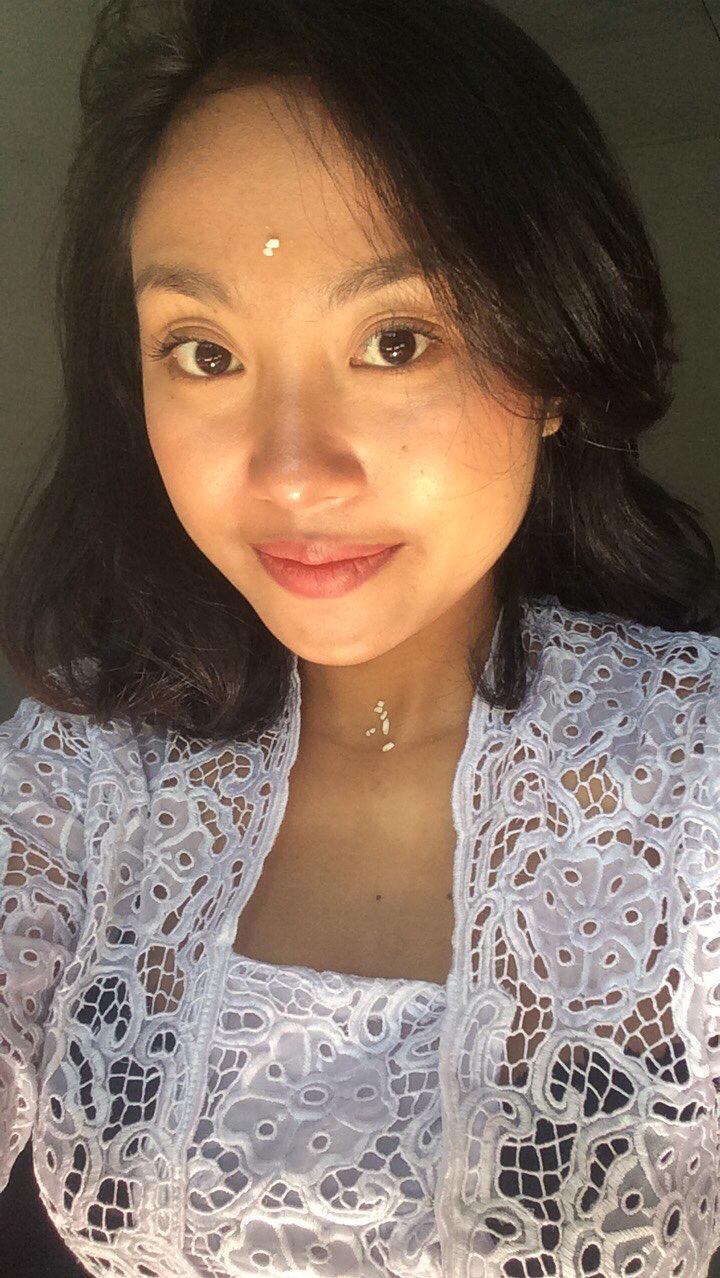Padi dan Beras: Tantangan Kebijakan Pangan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia
(Oleh: Tommy Gunawan, S.H)
(Pengurus DPD Perpadi Provinsi Lampung)
Kedaulatan pangan merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia yang strategis, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan tetapi juga pada kesejahteraan petani sebagai produsen utama. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya dalam produksi beras, yang merupakan makanan pokok bagi mayoritas penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, produksi beras nasional mencapai 32,3 juta ton, namun terdapat ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi yang menghambat pencapaian swasembada pangan. Permasalahan ini mencakup kebijakan harga gabah yang tidak konsisten, rendahnya daya saing penggilingan padi kecil, hingga peran pemerintah dan Bulog yang belum optimal dalam menyerap hasil panen.
Masalah yang kerap dihadapi oleh petani dan penggilingan padi kecil sangat mempengaruhi kelancaran distribusi pangan di Indonesia. Data dari Perpadi mencatat bahwa 60% dari 182 ribu penggilingan padi di Indonesia masih tergolong kecil dan tidak memiliki fasilitas pengering (dryer), yang mengakibatkan kualitas gabah yang dihasilkan menjadi rendah dan harga jual yang tidak stabil. Di sisi lain, kebijakan harga gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kilogram tidak selalu diterima petani, karena harga yang berlaku di lapangan sering kali lebih rendah. Ketidakmampuan Bulog dalam menyerap hasil panen secara maksimal juga menjadi masalah besar, di mana pada 2023, Bulog hanya mampu menyerap 1,5 juta ton dari target 2,4 juta ton beras nasional
Tulisan ini akan mencoba mengulas permasalahan yang ada mulai dari ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi pangan, kesulitan yang dihadapi oleh petani dan penggilingan padi kecil, hingga peran pemerintah melalui Badan Bulog yang belum maksimal. Pembahasan ini akan mengarah pada solusi konkret untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang sesungguhnya. Solusi tersebut meliputi realisasi kebijakan harga gabah yang tepat, pemberian dukungan teknologi bagi penggilingan padi kecil, serta penguatan peran Bulog dalam menyerap dan mendistribusikan beras. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan petani yang lebih baik.
Masalah yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pangan
Ketidakpastian Harga Gabah. Ketidakpastian harga gabah menjadi masalah utama bagi petani. Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram, di lapangan harga yang diterima petani sering kali lebih rendah, bahkan mencapai Rp 5.500 hingga Rp 6.000 per kilogram. Hal ini terjadi karena adanya perantara atau tengkulak yang membeli gabah dengan harga lebih murah atau ketidaktahuan petani mengenai harga pasar yang seharusnya. Ketidakpastian harga ini membuat petani kesulitan merencanakan pendapatan mereka, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan mereka dan ketahanan pangan secara keseluruhan.
Keterbatasan Infrastruktur Penggilingan Padi Kecil. Sebagian besar penggilingan padi di Indonesia adalah usaha kecil yang tidak dilengkapi dengan teknologi modern, seperti dryer (alat pengering). Tanpa teknologi yang memadai, kualitas gabah yang dihasilkan tidak stabil, dan hasilnya sering kali memiliki kadar air yang tinggi, sehingga kualitas beras yang dihasilkan juga rendah. Keterbatasan infrastruktur ini membuat penggilingan padi kecil kesulitan bersaing dengan penggilingan besar yang sudah dilengkapi dengan teknologi canggih. Akibatnya, penggilingan kecil sulit mendapatkan harga yang baik dan berisiko kehilangan pasar.
Birokrasi dalam Sistem Penyerapan Gabah. Proses penyerapan gabah yang melibatkan banyak pihak, seperti petani, kelompok tani (gapoktan), dan Bulog, sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit. Meskipun kebijakan terbaru mengharuskan petani untuk menjual gabah melalui gapoktan yang bekerja sama dengan pabrik penggilingan besar yang telah dipilih oleh Bulog, sistem ini tidak selalu berjalan lancar. Beberapa penggilingan padi kecil tidak memiliki akses ke dalam sistem ini karena terbatasnya kemitraan dengan pabrik besar, dan terkadang gapoktan juga kesulitan dalam menyerap gabah dari petani secara efisien. Akibatnya, distribusi gabah tidak optimal dan banyak petani kesulitan menjual hasil panennya.
Tertinggalnya Penggilingan Padi Kecil. Penggilingan padi kecil yang tidak dapat berpartisipasi dalam sistem penyerapan gabah yang baru akhirnya menjadi korban dalam sistem distribusi yang ada. Karena tidak memiliki kapasitas atau akses untuk bekerjasama dengan Bulog atau pabrik besar, banyak penggilingan kecil yang terpaksa tutup karena kehilangan pasar. Selain itu, banyak penggilingan padi kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan kualitas gabah yang ditetapkan oleh Bulog, sehingga mereka tidak dapat memasok gabah mereka ke pasar yang lebih luas. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan dalam sektor perpadian dan berisiko mengurangi jumlah penggilingan padi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.
Ketidakjelasan Implementasi Kebijakan: Sebuah Tanda Tanya Besar
Pemerintah Indonesia terus mengeluarkan berbagai regulasi terkait pangan, namun sering kali kebijakan tersebut tidak sampai ke tujuan yang diharapkan. Salah satunya adalah kebijakan terkait harga gabah yang baru, yang meskipun menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi Rp 6.500 per kilogram, nyatanya masih banyak petani yang menerima harga jauh lebih rendah. Regulasi semacam ini menimbulkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dibuat? Apakah benar untuk kesejahteraan petani, atau sekadar alat politik yang tak lebih dari sekadar janji kosong?
Kebijakan yang mengharuskan petani menjual gabah melalui kelompok tani (gapoktan) yang bekerja sama dengan pabrik penggilingan besar juga memperlihatkan adanya kesenjangan yang semakin lebar. Penggilingan padi kecil yang tidak terintegrasi dalam sistem ini, terus terpinggirkan dan kesulitan dalam bersaing. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memperhitungkan realitas lapangan yang dihadapi oleh sebagian besar petani dan pelaku usaha kecil di sektor pangan. Tanpa ada solusi yang membumi untuk penggilingan kecil, regulasi yang dihasilkan malah semakin memperburuk ketimpangan yang ada.
Pada akhirnya, kedaulatan pangan yang dijanjikan hanya akan berakhir menjadi sebuah ilusi jika kebijakan yang ada tidak mampu menjangkau semua pihak yang terlibat. Ketidakmampuan dalam implementasi regulasi ini mencerminkan adanya masalah yang lebih besar, yakni ketidakmampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan. Tanpa keberpihakan yang nyata pada petani dan pelaku usaha kecil, swasembada pangan yang diharapkan hanya akan menjadi mimpi kosong belaka.
Solusi atas Problematika Kebijakan Pangan: Menuju Kedaulatan Pangan
Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan kedaulatan pangan, terutama dalam sektor padi dan beras. Namun, implementasi kebijakan yang masih terhambat oleh birokrasi, ketidakpastian harga, dan ketimpangan antara penggilingan besar dan kecil, menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu, solusi yang lebih terarah dan berbasis pada kenyataan lapangan perlu dikembangkan agar kebijakan pangan yang ada dapat memberi dampak positif dan mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan.
Sebagai langkah pertama, penulis mengacu pada pandangan ekonom pertanian, Amartya Sen, dalam bukunya Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981), yang menekankan bahwa krisis pangan lebih banyak disebabkan oleh ketidakadilan distribusi dan akses yang tidak merata, daripada masalah produksi itu sendiri. Mengikuti pemikiran ini, solusi pertama yang dapat diusulkan adalah peningkatan akses pasar bagi penggilingan padi kecil dan petani. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan mekanisme distribusi yang lebih fleksibel, yang tidak hanya melibatkan pabrik penggilingan besar yang ditunjuk oleh Bulog, tetapi juga memberi ruang bagi penggilingan kecil untuk terlibat dalam sistem yang ada. Kebijakan yang lebih inklusif, dengan memberikan dukungan teknologi dan pelatihan kepada penggilingan padi kecil, akan meningkatkan kualitas gabah dan daya saing mereka di pasar, sehingga meningkatkan harga yang diterima petani.
Selanjutnya, untuk mengatasi masalah ketidakpastian harga gabah, penulis merujuk pada pandangan Joseph Stiglitz dalam bukunya Globalization and Its Discontents (2002), yang menyarankan pentingnya intervensi pasar yang lebih efektif melalui kebijakan yang mengutamakan stabilitas harga dan pengawasan yang lebih ketat terhadap tengkulak dan perantara. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik perantara yang sering kali membeli gabah dengan harga rendah, serta memastikan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) benar-benar tercapai di tingkat petani. Hal ini akan mengurangi ketimpangan harga yang sering kali merugikan petani dan menciptakan pasar yang lebih stabil, di mana petani dapat merencanakan pendapatan mereka dengan lebih baik.
Selanjutnya, Kebijakan ini juga harus sejalan dengan upaya mengoptimalkan kapasitas penyerapan gabah oleh Bulog. Mengutip pandangan Michael Lipton dalam bukunya Why Poor People Stay Poor (1998), yang menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi dan memperbaiki sistem distribusi pangan untuk mencapai ketahanan pangan yang adil, pemerintah perlu mengurangi birokrasi yang menghambat kelancaran penyerapan gabah. Penyederhanaan prosedur dan pemberdayaan kelompok tani (gapoktan) menjadi kunci agar petani dapat menjual hasil panennya dengan lebih efisien. Melalui regulasi yang lebih mudah diakses dan lebih sedikit hambatan administratif, distribusi gabah dapat dilakukan lebih cepat dan lebih adil, sehingga mendukung ketahanan pangan yang lebih stabil.
Sehingga Pak Mentri Amran Sulaiman semakin fokus untuk mengatasi permasalahan dalam sektor pertanian, terutama yang berkaitan dengan padi dan beras. Yang katanya membawa visi untuk memperkuat sektor pertanian melalui pemberdayaan petani, penguatan sistem distribusi pangan, dan peningkatan teknologi pertanian. Dalam konteks kedaulatan pangan, Amran Sulaiman mendorong terciptanya sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis pada keberlanjutan. Ketersediaan pangan yang cukup dan merata, dengan stabilitas harga yang lebih baik, akan menjadi fondasi untuk mencapai swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Akhirnya, solusi yang dikembangkan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan petani tetapi juga sejalan dengan target Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dikenal dengan upayanya untuk mendorong Indonesia menuju swasembada pangan, khususnya dalam sektor padi dan beras. Dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penggilingan padi kecil, menciptakan stabilitas harga, dan menyederhanakan birokrasi dalam penyerapan gabah, Indonesia dapat menuju kedaulatan pangan yang sesungguhnya. Kebijakan ini tidak hanya akan berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada keberlanjutan produksi pangan dalam negeri, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung cita-cita swasembada pangan yang berkelanjutan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, meskipun sudah lebih dari 100 hari menjabat, harus menghadapi kenyataan bahwa kebijakan yang ada belum memberikan dampak signifikan pada petani kecil dan distribusi pangan secara menyeluruh. Penggilingan padi kecil tetap terpinggirkan, dan masalah ketidakpastian harga gabah serta distribusi yang kacau masih menjadi tantangan besar. Dengan berfokus pada langkah-langkah yang lebih terintegrasi dan menciptakan sistem distribusi yang lebih adil, pemerintah harus dapat mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada agar benar-benar bisa mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar menjadi retorika politik semata.


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co Gubuktulis.com
Gubuktulis.com surau.co
surau.co