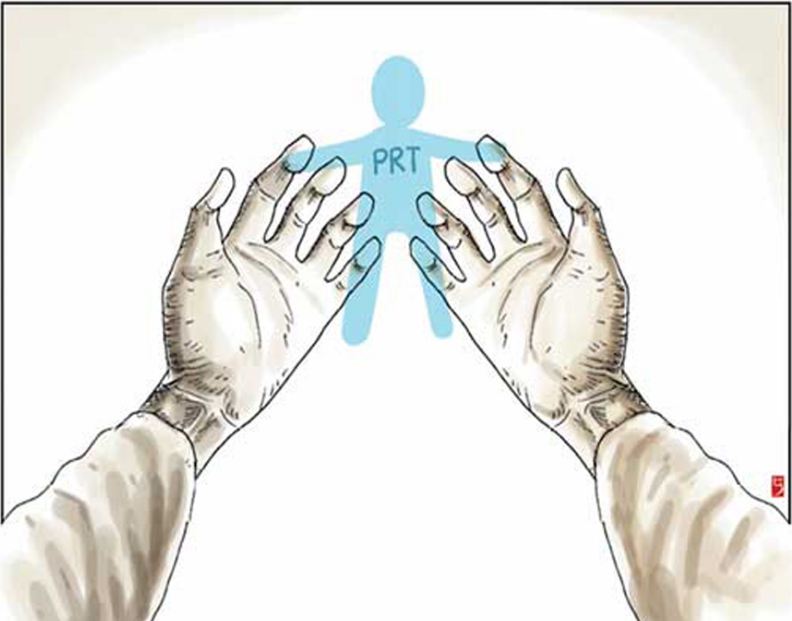
Willy Aditya: Pekerja Rumah Tangga dan Reproduksi Sosial
Kita biasa menyebutnya “pembantu”, “asisten rumah tangga”, bahkan “babu” atau “jongos” di beberapa waktu silam. Jika ditelusuri jauh ke belakang, mungkin kita akan mendapati mereka sebagai kelas sosial bernama “budak”. Terdengar peyoratif jika menggunakan standar sosial kita saat ini. Namun di zamannya, bagaimanapun, entitas mereka tetap diakui. Peran dan fungsi sosialnya juga tidak jauh berbeda: melaksanakan kerja-kerja rumah tangga. Akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri jika mereka mendapat status “merdeka” dari para pemiliknya. Namun tidak sedikit yang bingung jika status sosial itu mereka dapatkan. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan.
Kini, masa perbudakan telah sirna. Istilahnya bahkan mengandung implikasi hukum tertentu. Namun secara psikologis, tidak sedikit yang tetap memandang mereka sebagai kelas kedua dan memperlakukannya dengan alam pikir atau jatuh ke logika perbudakan: kerja nyaris 24 jam; pelaksana kerja-kerja kotor, dsb. Secara politis, entitasnya bahkan terus terhalang untuk mendapat pengakuan hukum negara.
Pekerja rumah tangga (PRT), begitu kini mereka disebut, sesungguhnya adalah entitas pengganti dari kerja-kerja harian anggota rumah tangga. Anehnya, saat disubstitusikan, nilai kerjanya menjadi rendah, longgar relasinya, namun dengan tingkat risiko dan kerentanan yang cukup tinggi.
Secara sosiologis, kata Sosiolog Robertus Robet, PRT adalah mereka yang bekerja dengan dua fungsi utama: mendukung atau membantu proses reproduksi sosial rumah tangga; serta mendukung/membantu berlangsungnya ekonomi-perawatan di dalam rumah tangga.
Dalam menjelaskan perannya dalam reproduksi sosial rumah tangga, Robet menunjukkan relasi sekaligus peran PRT terhadap majikannya yang begitu vital dan strategis. Terhadap mereka, PRT bahkan tidak hanya “menjual” tenaga semata, melainkan juga jasa. Untuk bisa memahami ini, kita harus melihat apa yang dikerjakan oleh PRT sebagai sesuatu yang terintegrasi dengan pekerjaan si pemberi kerja.
Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PRT mungkin bukan jenis pekerjaan produktif pada umumnya. Output pekerjaannya pun sulit untuk diukur. Akan tetapi, tanpa support atau bantuan dari PRT, karir dan kesuksesan si pemberi kerja sangat mungkin tidak akan terwujud. Ini karena PRT adalah pihak yang mengerjakan kerja-kerja rumah tangga yang tidak bisa dilakukan oleh si pemberi kerja. Karena itu, PRT sesungguhnya adalah bidang pekerjaan yang melakukan fungsi reproduksi sosial sekaligus memberikan dukungan langsung kepada reproduksi ekonomi di pemberi kerja.
Dalam bahasa yang lebih teknis, Robet menyebut peran PRT dalam fungsi ekonomi-perawatan seseorang. Dalam fungsi tersebut, PRT telah membantu memenuhi kebutuhan, terutama dalam bidang pengasuhan dan perawatan di dalam keluarga. Pekerjaan ini berfungsi penting karena menunjukkan fungsi yang sangat beragam dalam pekerjaanya. Hal ini pula yang sebenarnya membuat nilai kerjanya menjadi sangat tinggi. Namun karena fungsi dan nilai kerja semacam ini dipandang remeh karena sifat praktikalitasnya yang menyatu di dalam keluarga maka ia dianggap sebagai fungsi domestik “yang wajar” yang akibatnya tidak dihitung sebagai kerja yang sifatnya “produktif”.
Domestifikasi pekerjaan yang kebanyakan dilakukan oleh perempuan ini pada akhirnya membuat PRT terus berada dalam logika subordinasi. Posisi perempuan yang cenderung disubordinasi di dalam lingkungan sosial akhirnya merambat juga pada praktek subordinasi pekerjaan yang dilakukannya. Di Indonesia saat ini, profesi sebagai PRT tidak diakui dan tidak dapat dicatatkan di dalam KTP atau SIM, misalnya. Secara kultural, masyarakat umum pun lebih sering memandang peyoratif profesi ini lewat berbagai atribusi khasnya. Karena kerentanan status dan posisinya, PRT juga kerap mengalami tindak kekerasan para majikannya.
Upaya perlindungan
Ika Masriati adalah PRT berusia 19 tahun. Ia mengalami kerusakan pita suara akibat dianiaya majikannya. Bibir dan mulutnya membengkak akibat dipaksa minum air panas karena dituduh mencuri ponsel majikannya, di Semarang Barat. Kasus Ika, hanyalah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran kemanusiaan yang terjadi terhadap para PRT. Sebab selain penganiayaan, kasus human traficking juga kerap mengiringi dunia rekrutmen PRT karena kerentanan regulasi yang ada.
Sayangnya, angka-angka laporan kasus yang terus bertambah itu hanya mengisi deret angka statistika semata. Upaya membuat payung hukum perlindungan pekerja rumah tangga terus menghadapi tembok penghalang. Baru tahun 2015 yang lalu, Kementerian Ketenagakerjaan membuat payung hukum dan pengakuan terhadap pekerja rumah tangga lewat peraturan menteri (Permen). Itupun setelah lembaga-lembaga internasional terus mendesaknya karena makin banyaknya kasus kekerasan terhadap PRT Indonesia di luar negeri. Sayangnya, permenaker sebagai payung hukum PRT pun tetap menempatkan mereka sebagai sektor informal.
Sementara itu, jutaan PRT migran kita atau biasa disebut TKI yang berada di negeri tetangga semisal di Malaysia, Singapura, dan Hongkong, justru sudah diangap menjadi sektor formal. Keberadaannya yang diakui sebagai pekerja itu menjadikannya jauh lebih terlindungi dibanding mereka yang bekerja di negara-negara yang tidak mengakui mereka sebagai pekerja.
Berbagai dialektika ini mengantarkan banyak elemen, pihak, serta pemangku kepentingan merumuskan sebuah payung hukum yang lebih memberi perlindungan sekaligus pengakuan terhadap entitas PRT sebagai kelompok dengan peran dan fungsi yang ternyata strategis dalam relasi reproduksi sosial dan ekonomi.
Relasi yang unik
Usaha membentuk RUU PRT sebenarnya sudah dimulai sejak 16 tahun yang lalu. Namun harus diakui, ada kegamangan dan ketakutan yang membayangi para pembuat kebijakan terkait RUU tersebut. Bayangan industrialis yang serba kaku dengan berbagai peraturan dan konsekuensinya, membuat banyak legislator skeptis terhadapnya. RUU PRT yang per 16 Juli 2020 kemarin mestinya sudah bisa menjadi RUU inisiatif DPR RI itu pun harus tertunda kembali. Padahal RUU ini memiliki keunikan tersendiri.
Meski mengakui PRT sebagai pekerja, RUU ini tetap berasas kekeluargaan dan tetap mengedepankan relasi kultural-sosiologis masyarakat Indonesia. Relasinya tidak akan kaku sebagaimana hubungan industrialis pada umumnya. Apalagi dalam faktanya, kehidupan para pekerja di Indonesia pun ternyata tidak benar-benar dalam hubungan industrialis yang saklek. Selalu ada hubungan kultural yang terjadi. Praktik uang kerahiman sebagai santunan perusahaan terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan adalah contoh paling sederhananya.
Walhasil, berbagai ketakutan atau kekhawatiran untuk meloloskan RUU ini menjadi produk legislasi negara sesungguhnya tidak beralasan. Sebagaimana Pancasila yang digali dari taman sari berbagai kebudayaan Nusantara, RUU PRT juga disusun dengan berbagai sudut pandang dan senantiasa memperhatikan aspek kultural masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, RUU PRT disusun sebagai manifestasi dari upaya membangun kehidupan yang berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ibrahim AS memuliakan seorang budak bernama Hajar dengan menikahinya. Lewat Hajar, lahir Ismail AS yang banyak memberi teladan akan kemuliaan berkorban. Yusuf AS pernah menjadi pelayan Raja Al Aziz hingga akhirnya diangkat menjadi penasihat raja dan kemudian diangkat oleh Tuhan sebagai nabi.
Bung Karno memuliakan pengasuhnya dengan menjadikan nama Sarinah di salah satu judul bukunya. Nama itupun dipakai oleh Bung Karno sebagai nama pusat perbelanjaan nasional yang hingga kini masih berdiri, sebagai simbol keberdikarian ekonomi bangsa.
Jika para nabi, orang-orang mulia, hingga proklamator kemerdekaan bangsa saja begitu memuliakan orang-orang yang pernah menjadi pengasuhnya, pembantunya, mengapa kita tidak mengikuti jejak luhur itu dengan memuliakan mereka lewat sebuah perundangan demi terjaganya harkat dan martabatnya sebagai manusia?
Artikel ini sebelumnya terbit di: willyaditya.com/memuliakan-kaum-sarinah/


 Rctiplus.com
Rctiplus.com pewartanusantara.com
pewartanusantara.com Jobnas.com
Jobnas.com Serikatnews.com
Serikatnews.com Langgar.co
Langgar.co Beritautama.co
Beritautama.co Gubuktulis.com
Gubuktulis.com surau.co
surau.co






